Jakarta, inca-construction.co.id – Dalam dunia teknologi yang sekarang serba agile, ringan, dan modular, istilah “monolitik” sering terdengar… kuno. Tapi percaya atau tidak, banyak perusahaan raksasa yang hingga kini masih berjalan di atas arsitektur monolitik. Bahkan beberapa startup yang sedang meroket pun diam-diam memilih monolit sebagai fondasi awal mereka.
Lalu, sebenarnya apa sih arsitektur monolitik itu?
Secara sederhana, arsitektur monolitik adalah gaya pembangunan aplikasi di mana seluruh komponen—dari user interface, logika bisnis, hingga akses database—dijadikan satu kesatuan dan dijalankan dalam satu proses. Bayangkan seperti gedung tua satu lantai yang menyatukan dapur, ruang tamu, dan kamar tidur tanpa sekat. Sekali renovasi, semuanya harus dibongkar.
Saya ingat betul obrolan saya dengan Faiz, seorang software engineer di sebuah BUMN energi digital. “Sistem kita masih monolitik dari zaman 2012. Tapi anehnya, tetap stabil dan nggak rewel. Emang berat kalau mau ubah, tapi selama jalan, ya kita rawat,” katanya sambil tertawa kecil.
Dan Faiz tidak sendiri. Banyak tim teknologi, dari e-commerce sampai layanan kesehatan, memilih mempertahankan arsitektur ini karena… yah, monolitik itu sederhana dan langsung to the point. Setidaknya, di awal.
Namun, seiring waktu dan pertumbuhan skala, arsitektur ini bisa berubah jadi monster yang rumit. Di sinilah dilema dimulai.
Menyelami Anatomi Arsitektur Monolitik—Bagaimana Ia Bekerja?
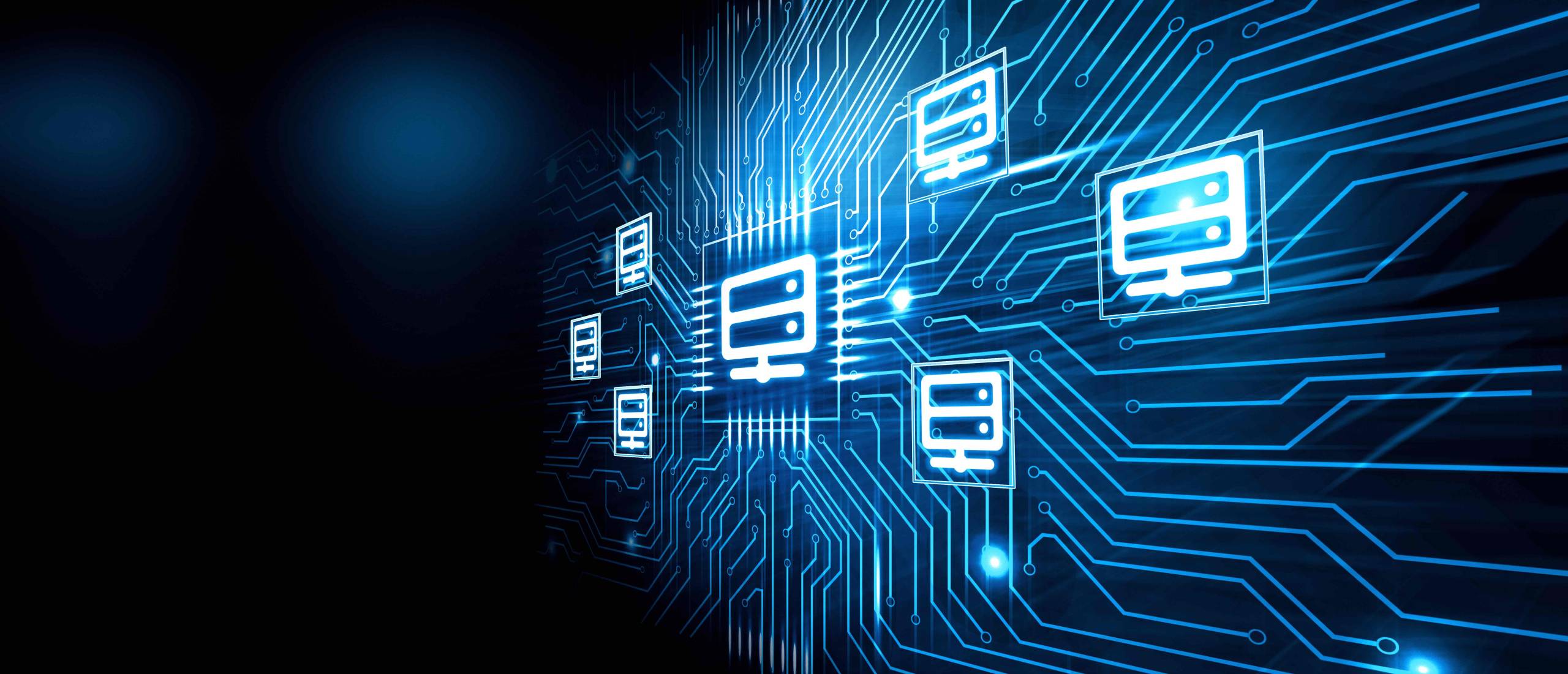
Untuk memahami monolitik, mari kita bayangkan kamu membangun sebuah aplikasi e-commerce sederhana.
Dalam satu aplikasi ini, kamu akan menemukan:
-
Modul login pengguna
-
Halaman katalog produk
-
Keranjang belanja
-
Fungsi pembayaran
-
Backend untuk admin
Jika dibangun secara monolitik, semua fitur tersebut dikembangkan dalam satu codebase, dikompilasi bersama, dan dijalankan dalam satu proses aplikasi. Saat kamu deploy ke server, seluruh aplikasi ikut “naik” bersama.
Tidak ada pemisahan layanan secara fisik. Satu file .war atau .jar (bagi yang akrab dengan Java), atau satu image Docker besar, membawa semua hal di dalamnya.
Kelebihan dari pendekatan ini?
1. Cepat Dibangun
Untuk proyek awal, kamu tidak perlu mikirin komunikasi antar layanan, orchestrator, atau API gateway. Fokus saja pada fitur.
2. Mudah Dites di Awal
Kamu bisa melakukan unit test atau end-to-end test langsung di satu tempat, tanpa khawatir soal sinkronisasi antar service.
3. Deploy Sekali Jadi
Satu kali push ke server, seluruh sistem terupdate. Cocok untuk tim kecil atau MVP.
Tapi seperti rumah yang dibangun tanpa fondasi bertingkat, begitu penghuni bertambah dan ruang dibutuhkan, kamu akan merasa sesak. Sekali kamu ingin renovasi satu ruangan (katakanlah modul pembayaran), bisa-bisa seluruh rumah ikut goyang.
Itu yang terjadi pada aplikasi monolitik berskala besar. Ukuran codebase membengkak, testing makin lambat, dan satu bug kecil bisa menjatuhkan sistem utuh. Welcome to the monolith dilemma.
Ketika Monolitik Menjadi Beban—Kelemahan dan Batasan
Sebuah startup fintech lokal pernah mengalami hal ini. Mereka memulai dengan cepat menggunakan monolitik karena hanya ada 3 engineer di awal. Tapi 2 tahun kemudian, user sudah ratusan ribu, fitur makin kompleks, dan mereka mulai kewalahan.
1. Deploy Jadi Mimpi Buruk
Setiap kali ingin merilis satu fitur kecil, mereka harus build ulang dan test seluruh aplikasi. Sekali ada kesalahan di modul yang tidak terkait, bisa membuat checkout transaksi gagal. Stress? Jelas.
2. Terlalu Bergantung pada Satu Teknologi
Monolitik membuat kamu “terjebak” dalam satu stack. Mau coba pindah dari PHP ke Go di satu bagian? Nggak bisa. Semua harus diubah. Ini menyulitkan adopsi teknologi baru secara modular.
3. Skalabilitas Terbatas
Kalau modul katalog butuh scaling karena trafik tinggi, kamu tetap harus menaikkan seluruh aplikasi. Tidak efisien dan mahal.
4. Kepemilikan Kode Tak Jelas
Codebase besar dengan banyak fitur membuat tim sulit membagi tanggung jawab. Tiba-tiba semua engineer jadi “full-stack” secara terpaksa karena semua fitur saling terkait.
Seperti kata Dimas, seorang lead dev di perusahaan logistik: “Aplikasi kita tuh kayak spaghetti. Tarik satu ujung, nyangkut di mana-mana. Monolitik itu gampang buat awal, tapi bisa jadi jebakan kalau nggak disiapkan buat scale.”
Apakah Monolitik Masih Relevan? Jawabannya: Ya, Tapi…
Meski banyak suara yang mendorong migrasi ke microservices atau serverless, monolitik belum mati. Bahkan beberapa perusahaan justru sengaja memulai dengan monolitik, dan baru memecah jadi layanan kecil ketika skala benar-benar menuntut.
Kenapa?
1. Monolitik Masih Efisien di Skala Tertentu
Tidak semua aplikasi butuh microservices. Untuk aplikasi internal perusahaan, sistem informasi sekolah, atau platform komunitas kecil, monolitik jauh lebih mudah diatur dan hemat biaya.
2. Tidak Semua Tim Siap dengan Kerumitan Microservices
Bayangkan kamu harus mengelola 10 layanan kecil, masing-masing dengan service discovery, circuit breaker, logging terpisah, dan monitoring. Tanpa skill dan tools yang matang, kamu bisa pusing sendiri.
3. Migrasi Butuh Waktu dan Biaya
Migrasi dari monolit ke microservices bukan soal ganti struktur folder. Ini bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahun. Perusahaan harus punya alasan kuat sebelum memutuskan lompat ke sana.
Netflix, misalnya, dulu juga memulai dari sistem monolitik. Baru setelah mengalami bottleneck besar pada streaming engine-nya, mereka memecah layanan. Prosesnya makan waktu bertahun-tahun dan penuh trial-error.
Jadi, jawabannya bukan “tinggalkan monolitik”, tapi “bangun monolitik yang modular dan siap evolusi.”
Strategi Mengelola dan Mengembangkan Arsitektur Monolitik secara Sehat
Kalau kamu (atau perusahaanmu) sudah terlanjur menggunakan monolitik, jangan panik. Ada banyak cara untuk tetap menjaga sistem tetap sehat, scalable, dan maintainable.
1. Buat Layering yang Jelas
Pisahkan domain secara logis. Misalnya, pisahkan modul user, transaksi, dan notifikasi dalam package atau folder berbeda. Meskipun masih dalam satu codebase, atur batas tanggung jawab yang rapi.
2. Gunakan Feature Toggle
Hindari deployment besar dengan risiko tinggi. Feature toggle bisa membantu uji coba di sebagian user tanpa mengganggu sistem utama.
3. Logging dan Monitoring yang Tertata
Jangan menunggu error besar. Gunakan tools seperti Sentry, Datadog, atau ELK stack untuk terus memantau performa sistem dan error kecil sebelum menjadi besar.
4. Uji Coba Migrasi Modular
Kalau ingin transisi ke microservices, jangan langsung pecah semua. Mulai dari layanan kecil yang tidak tergantung ke banyak modul lain. Misalnya: layanan notifikasi SMS atau billing.
5. Dokumentasi dan Kepemilikan Kode
Tentukan siapa bertanggung jawab atas tiap modul. Buat dokumentasi teknis yang jelas. Ini menghindari “bus factor” — kalau satu engineer resign, seluruh pengetahuan ikut hilang.
Yang terpenting: jangan malu menggunakan monolitik. Yang penting adalah menggunakannya dengan cerdas.
Kesimpulan: Monolitik Bukan Musuh, Tapi Teman yang Perlu Dipahami
Dalam dunia arsitektur perangkat lunak, tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Monolitik adalah gaya yang sudah terbukti kokoh selama bertahun-tahun. Bahkan hingga hari ini, banyak sistem penting di dunia masih beroperasi di atas arsitektur ini.
Namun, seperti bangunan tua, ia perlu dirawat, dimodernisasi, dan kadang direnovasi sebagian.
Jangan latah ikut tren tanpa tahu kebutuhan. Yang paling penting adalah membangun sistem yang sesuai dengan tim, sumber daya, dan visi bisnis. Apakah itu monolitik, microservices, atau hybrid—yang terpenting adalah kesadaran arsitektur sejak awal.
Seperti kata pepatah, “Kamu boleh bangun rumah dari kayu atau batu bata, yang penting fondasinya kuat dan tahu cara merawatnya.”
Baca Juga Artikel dari: Manajemen Logistik Konstruksi: Proyek yang Sering Diabaikan
Baca Juga Konten dengan Artikel Terkait Tentang: Arsitektur

